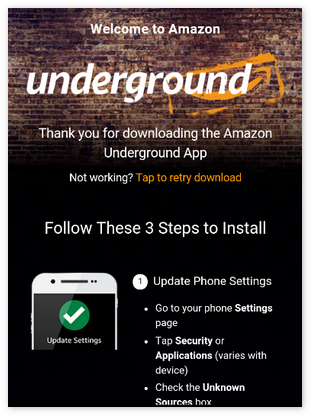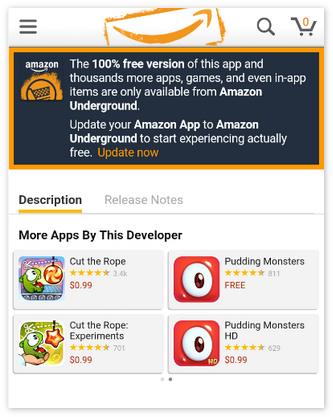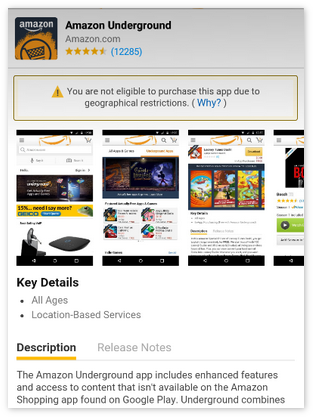[Ilustrasi: Justin Poliachik – justinpoliachik | flickr.com]
Banyak masyarakat yang bersimpati dengan pengemudi Gojek. Menurut sebagian orang kelakukan ojek pangkalan itu tidak pantas. “Cari makan ya harusnya adil aja, tidak perlu mengaku-ngaku sebagai penguasa wilayah tertentu. Suka-suka konsumen mau menggunakan yang mana.” Kira-kira begitu pendapat mereka.
Sampai hari ini beberapa daerah dipasangi spanduk oleh pengemudi ojek pangkalan. Isi spanduknya jelas, melarang Gojek beroperasi di wilayah tersebut. Salah satu yang cukup terkenal di daerah Apartemen Kalibata City, Jakarta. Tidak bisa dipungkiri kalau itu salah satu bentuk intimidasi terhadap ojek berbasis aplikasi.
Nah, dalam tulisan saya sebelum ini, saya mengulas bagaimana dugaan saya mengenai fase perubahan ojek berbasis aplikasi (Gojek dan GrabBike) secara sosial. Ternyata bukan isapan jempol. Salah satu dugaan saya itu sudah terjadi.
Kejadiannya di area seputar salah satu apartemen di daerah Jakarta Barat. Awalnya hanya pengemudi Gojek yang mangkal disitu. Lama kelamaan mulai ramai pengemudi GrabBike. Nah karena promosi GrabBike hanya Rp 5.000 (dibanding Gojek yang 15.000), akhirnya lambat laun penghuni apartemen memilih Grab Bike.
Dulu penghuni apartemen keluar pintu belok kanan (tempat pengemudi Gojek mangkal), belakangan hampir semua belok kiri (tempat pengemudi Grab Bike mangkal). Pengemudi Gojek pun cemburu. Akhirnya salah satu dari mereka ada yang mendatangi pengemudi Grab Bike yang mangkal. Meminta agar mereka tidak lagi mangkal di situ. Ujung-ujungnya ribut, hingga berkelahi. Untung ada satpam, sehingga berhasil dilerai. Kalah jumlah, akhirnya salah satu kelompok pindah mangkal ke area menara apartemen yang lain.
Jadi, kalau dulu pengemudi Gojek diintimidasi oleh ojek pangkalan, ternyata sebagian dari mereka sudah belajar dari situ, gimana cara mengintimidasi pengojek lainnya.
Taksi
Kejadian seperti ini tidak hanya di urusan ojek sih. Di dunia taksi juga sama. Banyak titik-titik yang sudah “dikuasai” kelompok pengemudi taksi tertentu.
Salah satu contohnya, sudah jadi rahasia umum kalau nunggu kita tidak akan berhasil naik taksi Blue Bird di salah satu area dekat gerbang keluar tol Pasteur, Bandung. Pengemudi burung biru ini tidak ada yang berani ambil penumpang di situ. Karena di area itu sudah banyak nangkring taksi lokal. Cerita-cerita dari sopir sih, kadang dipukuli kalau sampai berani ngambil penumpang di daerah situ.
…
Yang jelas penularan penyakit seperti ini harus dicegah. Apalagi mengingat jumlah pengemudi ojek berbasis aplikasi ini sudah di sekitar angka ratus ribuan. Kalau sempat banyak yang tertular, terlalu sulit untuk mengobatinya.